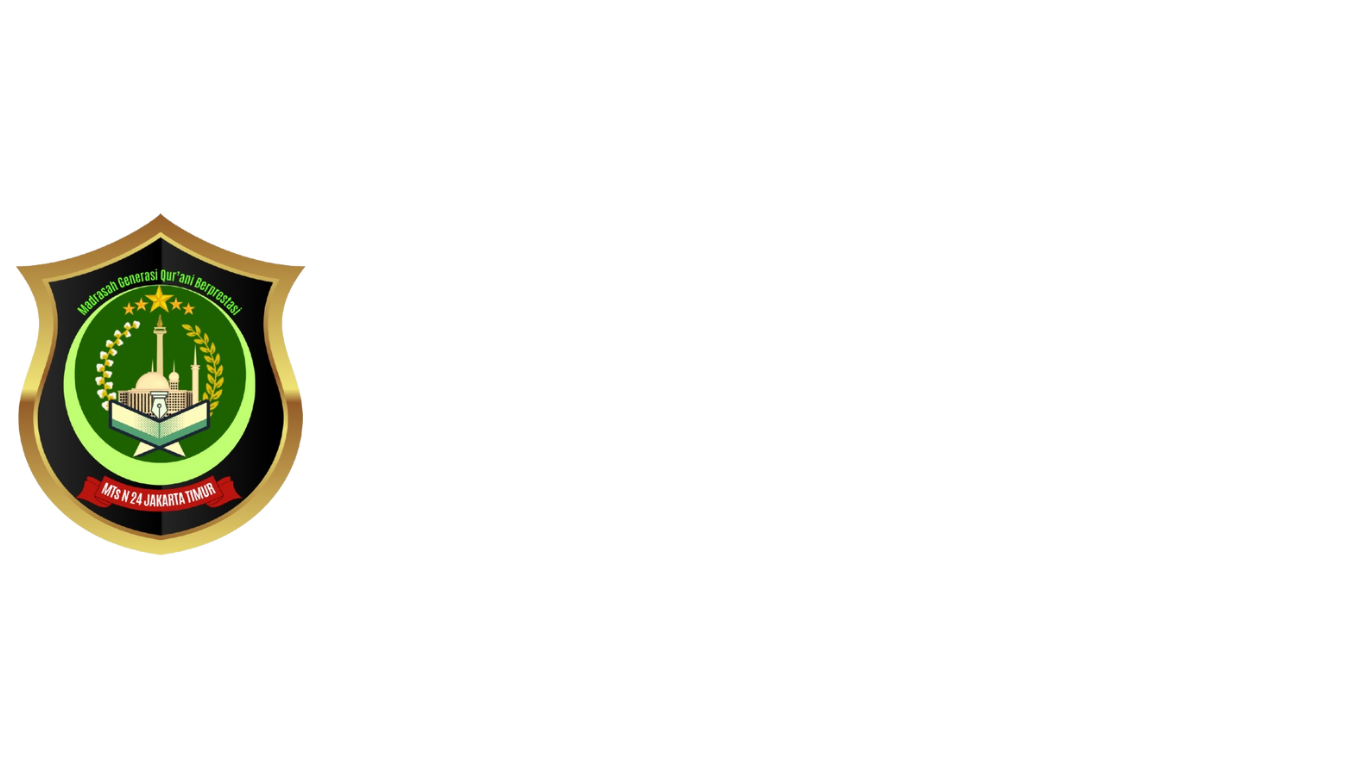Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, sebuah momen untuk mengenang Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh pelopor emansipasi wanita yang gagasan-gagasannya jauh melampaui zamannya. Namun, ironisnya, peringatan ini seringkali direduksi menjadi sekadar ritual mengenakan kebaya dan bersolek, seolah-olah esensi perjuangan Kartini terletak pada penampilan fisiknya semata. Dalam konteks ini, kita perlu menggali lebih dalam makna sebenarnya dari pernyataan Kartini, “Habis gelap terbitlah terang,” yang terinspirasi dari Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat ke-257 yang artinya, “Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman)…”
Merayakan Hari Kartini bukan sekedar “ritual bersolek,” karena Kartini sendiri bukanlah seorang yang gemar berdandan berlebihan. Kebaya dan konde yang dikenakannya lebih merupakan representasi identitasnya sebagai seorang putri Jawa yang lekat dengan tradisi, bukan semata-mata untuk menonjolkan keperempuanannya. Kartini justru dikenal dengan kesederhanaannya, meskipun terlahir sebagai bangsawan. Dalam surat-suratnya, ia lebih banyak membahas tentang ketidakadilan sosial, pendidikan, dan hak-hak perempuan. Ia ingin agar perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berpendidikan, sehingga mereka bisa mengubah nasib mereka sendiri.
Kehebatan Kartini terletak pada kedalaman pemikiran dan keberaniannya untuk melampaui batas-batas sosial yang mengekang kaum wanita pada masanya. Melalui surat-menyurat intensif dengan sahabatnya di Belanda, ia menuangkan kegelisahan hatinya, ide-ide progresifnya, dan visinya tentang kemajuan kaumnya. Dalam surat-surat tersebut, Kartini tidak hanya berbicara tentang aspirasi pribadinya, tetapi juga memperjuangkan hak-hak perempuan secara umum. Ia ingin agar perempuan tidak hanya dianggap sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat. Misalnya, ia mengusulkan agar perempuan diberikan akses pendidikan yang lebih baik, agar bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Lebih jauh lagi, Kartini tidak hanya berkutat pada isu perempuan, tetapi juga memiliki ketertarikan yang mendalam pada agama. Sebuah fakta yang mungkin kurang banyak disorot adalah interaksi intelektual Kartini dengan ulama besar Kyai Sholeh Darat dari Semarang, seorang ulama yang menjadi guru K.H. Hasyim As’ari (pendiri NU), K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhamadiyah), dan pemegang lisensi sebagai pengajar di Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke kisah Kartini. Ia merasa tidak puas hanya membaca Al-Qur’an tanpa memahami maknanya. Ia bahkan meminta Kyai Sholeh Darat untuk menerjemahkan Al-Qur’an ke dalam bahasa Jawa agar lebih mudah dipahami. Inisiatif ini menunjukkan betapa besar dahaga Kartini akan ilmu pengetahuan, termasuk pemahaman yang mendalam tentang ajaran agamanya. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa Kartini tidak hanya mencari pengetahuan untuk dirinya sendiri, tetapi juga berusaha untuk menyebarkan pengetahuan tersebut kepada orang lain, terutama perempuan di sekitarnya.
Keingintahuan Kartini terhadap makna Al-Qur’an selaras dengan seruan dalam kitab suci itu sendiri untuk terus mencari ilmu dan memahami ajaran-ajaran-Nya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mujadilah (58): 11, yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan bagaimana Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Semangat Kartini untuk memahami Al-Qur’an adalah cerminan dari perintah ini. Dalam pandangan Kartini, pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan kemajuan. Ia percaya bahwa dengan memahami ajaran agama secara mendalam, perempuan dapat menemukan kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan berkontribusi dalam masyarakat.
Lebih lanjut, Kartini dengan berani menyuarakan kritik terhadap praktik keagamaan yang justru menimbulkan dosa dan diskriminasi. Kata-katanya, “Agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama,” seolah relevan dengan realitas hari ini. Kita menyaksikan bagaimana konflik dan kebencian seringkali dipicu oleh interpretasi agama yang sempit dan eksklusif. Diskriminasi terhadap perempuan atas nama agama juga masih menjadi isu yang memprihatinkan. Dalam konteks ini, Kartini mengajak kita untuk berpikir kritis dan tidak menerima begitu saja segala sesuatu yang diajarkan oleh tradisi atau otoritas agama. Ia mendorong kita untuk mencari kebenaran dan keadilan, serta berani mengoreksi kesalahan yang ada dalam praktik keagamaan.
Buah pikiran Kartini menunjukkan bahwa fokusnya bukanlah pada tampilan fisik semata. Ia lebih memilih untuk “menghias diri dengan tafakur dan merenungi nasib kaumnya,” serta berjuang demi kemajuan peradaban bangsanya. Sikap dan pemikiran inilah yang seharusnya kita teladani. Dalam dunia yang semakin materialistis ini, seringkali kita terjebak dalam penampilan fisik dan mengabaikan nilai-nilai yang lebih dalam. Kartini mengingatkan kita bahwa esensi dari perjuangan tidak terletak pada apa yang kita kenakan, tetapi pada apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berpikir. Ia mengajak kita untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Sayangnya hari-hari ini sebuah pemikiran justru dianggap tidak penting, hanya teori saja dan tanpa aksi. Padahal pemikiran merupakan bagian tak terpisahkan dari sikap dan tindakan. Sikap Kartini berawal dari kegelisahan akan nasib kaumnya yang kemudian membuatnya berpikir, menulis, dan bertindak untuk melakukan perubahan.
Lantas, mengapa kita terus mengeksploitasi tampilan fisiknya? Mengapa peringatan Hari Kartini seringkali hanya berkutat pada konde, kebaya, dan riasan wajah hingga menyerupai boneka, bahkan di panggung-panggung kehormatan? Kartini jauh lebih dari sekadar raga. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, semangat untuk meraih ilmu pengetahuan, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Dalam konteks ini, kita perlu merenungkan kembali tujuan dari peringatan Hari Kartini. Apakah kita hanya ingin merayakan penampilan fisik, ataukah kita ingin menghormati warisan pemikiran dan perjuangan Kartini yang sesungguhnya?
Kita tentu tak ingin memperingati Hari Kartini hanya sebagai seremoni mengenakan pakaian adat, tetapi sebagai momentum untuk merenungkan kembali esensi perjuangannya. Mari kita teladani semangatnya dalam mencari ilmu, memperjuangkan kesetaraan, dan berani mengkritisi segala bentuk ketidakadilan, termasuk yang berlindung di balik nama agama. Dengan demikian, kita baru benar-benar menghormati warisan Kartini yang sesungguhnya. Sebuah warisan yang mengajak kita untuk terus bergerak maju, menggali ilmu, dan berjuang untuk keadilan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang di sekitar kita. Mari kita jadikan semangat Kartini sebagai pendorong untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, sehingga cita-cita emansipasi yang ia impikan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita.